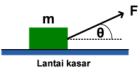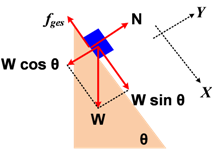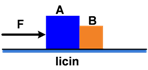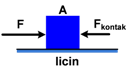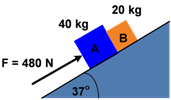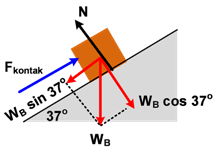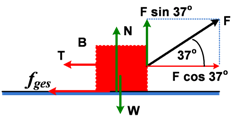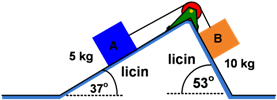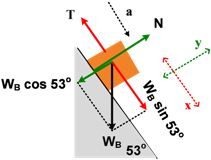Mengembangkan Karakter Konservasi
Memasuki kehidupan global, tantangan bagi eksistensi mahasiswa sangatlah berbeda dengan era sebelumnya. Kehidupan global yang menawarkan budaya-budaya hedonisme, materialisme, kapitalisme, pragmatisme, akan dengan mudah mengikis ideologi idealisme yang selama ini menjadi ruh bagi kehidupan mahasiswa, jika hal ini tidak dilakukan maintening secara tepat.
Hal tersebut di atas perlu memperoleh perhatian, oleh karena gejala-gejala mulai terkikisnya idealisme mahasiswa sedikit banyak mulai tampak. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di tahun 2011, memperoleh gambaran corak mahasiswa, yang terbagi ke dalam lima kelompok. Pertama adalah kelompok idealis konfrontatif, dimana mahasiwa tersebut aktif dalam perjuangannya menentang kemapamanan melalui aksi demonstrasi. Kedua, kelompok idealis realistis adalah mahasiwa yang memilih koperatif dalam perjuangannya menentang kemapanan. Ketiga, kelompok oportunis adalah mahasiswa yang cenderung mendukung pemerintah yang berkuasa. Keempatadalah kelompok profesional, yang lebih berorientasi pada belajar atau kuliah. Kelimaadalah kelompok rekreatif yang berorientasi pada gaya hidup yang glamour dan menyukai pesta. Yang menarik dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kelompok rekreatif memiliki populasi yang paling besar, yaitu mencapai angka 90%.
Hal ini lah yang menjadikan perlunya kampus memiliki “nilai dasar”, yang dapat melakukan maintening terhadap idealisme dan peran mahasiswa sepanjang zaman. Mahasiswa harus disadarkan akan pentingnya memiliki dan meyakini terhadap sistem nilai yang menjadi dasar landasan mereka dalam beraktifitas, meraih cita-cita masa depan yang gemilang.
Konservasi, pilihan nama yang melekat pada Universitas Negeri Semarang, memiliki kandungan nilai yang sangat mendalam. Konservasi tidak hanya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik semata, terkait dengan relasi antara manusia dengan alam, melainkan juga mencakupi tata nilai yang luas dan universal. Dalam kajian bahasa, “Conservation” (con berarti together dan servare berarti save) memiliki arti upaya memelihara apa yang dipunyai secara bijaksana. Terdapat tiga aktifitas di dalamnya yaitu protection, preservation, and sustainable use
Dalam konteks demikian, maka hak dan kewajiban menjadi penyangga utama sikap dan perilaku manusia, yaitu bahwa apa yang kita peroleh haruslah seimbang dengan apa yang kita berikan. Sudah tentu itu dalam makna yang seluas-luasnya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tidak hanya pada hal-hal yang bersifat ekonomis saja, akan tetapi dalam relasi antara manusia dengan alam sekitar. Menghirup udara segar, menikmati kesejukan pepohonan, menikmati kicauan burung nan menawan; merupakan hak yang kita peroleh dari alam semesta. Oleh karena itu sebagai imbangannya adalah kita harus memelihara, melindungi, dan melestarikannya.
Ada empat nilai utama dalam konservasi yang hendak ditanamkan pada para mahasiswa ; yaitu jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Inilah nilai-nilai yang sangat indah. Ketika kejujuran, kecerdasan, kepedulian, dan tangguh terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa melalui relasi dengan alam semesta; dengan pepohonan, burung-burung, air, udara, dan sudah tentu dengan sesama manusia; maka akan terinternalisasikan nilai-nilai itu pada mereka sebagai sebuah moral knowing, moral feeling, dan moral action. Melalui proses internalisasi nilai-nilai konservasi itu diharapkan pada gilirannya akan tumbuh berkembang nafas-nafas spiritualitas. Mereka tidak sekedar mencintai dan bertanggung jawab terhadap alam semesta, melainankan juga melakukannya terhadap penciptanya; pencipta alam semesta.
Meminjam terminologi dari Schopenhauer, kecintaan dan kepedulian ini disebut dengan compassion, yaitu cinta kasih, empati, dan simpati. Cinta kasih ini, menurutnya tidak hanya berdimensikan profane belaka, tetapi juga berspiritkan sakralitas. Schopenhauer menyebutnya sebagai all encompassing oneness, yang merupakan jati diri yang sejati manusia.
Pada tataran ini Schopenhauer sudah menunjuk pada kesadaran metafisis, bahwa kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar didasari oleh adanya “amanah ilahiyah”. Orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, melakukan upaya pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian adalah karena adanya perintah Tuhan untuk itu. Kesadaran pada tingkat inilah yang kemudian melahirkan berbagai ragam nilai kemanusiaan yang universal.
Collective consciousness atas nilai konservasi pada para mahasiswa ini harus dirawat sedemikian rupa agar berkembang secara sempurna. Jika pun kelak mereka lulus sebagai sarjana, akan menjadilah mereka sebagai kader-kader konservasi yang handal, dan siap mengabdikan diri pada bangsa melalui nilai-nilai konservasi yang mereka yakini. Pembinaan collective consciousness, haruslah merupakan upaya yang komprehensif, dengan multy approach. Meminjam analisis moral dari Kurtines (2004), ada tiga pendekatan pembinaan yaitu Cognitive Moral Development, Affective Moral Development, dan Behavior Moral Development .
Pertama, perlu dilakukan upaya perubahan struktur kognisi terlebih dahulu agar para mahasiswa memahami akan arti pentingnya nilai-nilai konservasi. Menurut pendekatan Cognitive Moral Development, dengan diketahuinya arti penting nilai-nilai konservasi oleh para mahasiswa, diharapkan akan tumbuh kesadaran dan kesiapan untuk menerima tata nilai tersebut menjadi miliknya sendiri (internalisasi nilai). Kesadaran dan internalisasi nilai yang berawal dari pemahaman akan tata nilai tersebut (struktur kognisi) akan memiliki kekuatan yang otentik, sebagai buah dari proses pembelajarannya (learned behavior). Masuknya mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup pada struktur kurikuler, sangat tepat untuk melakukan pembinaan collective consciousness atas nilai konservasi, pada kegiatan-kegiatan formal perkuliahan.
Selain upaya character building melalui perubahan struktur kognisi, tidak kalah pentingnya adalah melalui pendekatan intuisi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membawa imajinasi dan suasana hati para mahasiswa pada heroisme tata nilai konservasi. Hal inilah yang ditekankan oleh pendekatan Affective Moral Development,yaitu menanamkan nilai melalui aras afektif, berupa sentuhan-sentuhan perasaan, imajinasi, dan intuisi. Proses pembinaan afektif ini membutuhkan strategi tersendiri yang berbeda dengan proses-proses pembinaan kognitif. Para pimpinan dan para dosen dituntut untuk mempunyai kepiawaian dalam mengelola strategi pendekatan yang dilakukannya. Metode-metode out bond, games, perkuliahan di luar kelas, dan sejenisnya merupakan aplikasi dari pendekatan ini.
Selanjutnya pendekatan Behavior Moral Development memandang bahwa internalisasi nilai dilakukan melalui pembiasaan (conditioning/habituation). Kendatipun pendekatan ini berawal mula dari percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada seekor binatang, akan tetapi pendekatan ini sangat relevan dengan upaya penanaman nilai. Seorang mahasiswa yang dibiasakan tertib dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-harinya, pada akhirnya akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Pada gilirannya nanti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya tersebut akan mengendap menjadi tata nilai milik dirinya sendiri. Manakala mereka melakukan suatu tindakan di luar kebiasaannya, mereka akan merasa bersalah.
Ketiga pendekatan pembinaan nilai tersebut akan memiliki efektifitas tinggi ketika dilakukan secara simultan. Artinya pembinaan karakter (character building) dilakukan secara komprehensif, meliputi pengubahan struktur kognisi, sentuhan-sentuhan emosional, dan penciptaan lingkungan yang kondusif.
Melalui dialog-dialog dengan para mahasiswa, baik dalam pertemuan formal maupun informal pada umumnya mereka mengaku merasa bangga dengan universitas konservasi. Kebanggaan yang diutarakan para mahasiswa ini merupakan salah satu indikator kuatnya collective consciousness mengenai konservasi di kalangan mereka.
Keberadaan universitas “konservasi” pun merupakan ikhtiar mencari solusi dari persoalan carut marutnya kondisi lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Isu lingkungan fisik misalnya, menjadi keprihatinan semua orang khususnya adalah para mahasiswa.